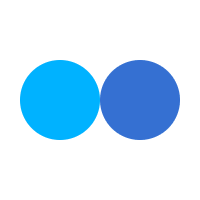Data terkait kondisi terkini infeksi parasit, termasuk kecacingan, di Indonesia masih sangat minim. Padahal, dengan kondisi iklim tropis yang hangat, faktor sosioekonomi yang kurang, dan tingkat pendidikan yang masih rendah, infeksi cacing diperkirakan masih tersebar luas di berbagai wilayah di Indonesia. Terdapat setidaknya empat jenis penyakit infeksi cacing yang masih ada di Indonesia, yakni filariasis, taeniasis, schistosomiasis, dan penyakit cacing tanah.[1]
Filariasis
Filariasis limfatik (FL) masih menjadi masalah kesehatan utama pada banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Sekitar 65% kasus filariasis di seluruh dunia ditemukan di Asia Tenggara. Filariasis limfatik hampir selalu bisa ditemukan di seluruh provinsi Indonesia dengan rentang prevalensi antara 0,5 hingga 27,6%. 236 kota dalam 514 distrik di Indonesia masih tercatat menjadi daerah endemis filariasis.
Data tahun 2017 menunjukkan bahwa jumlah penderita filariasis di Indonesia tercatat sebanyak 12.667 orang. Provinsi yang menunjukkan angka prevalensi tertinggi adalah Papua (3.047), disusul oleh Nusa Tenggara Timur (2.864), Papua Barat (1.244), Jawa Barat (907), dan Aceh (591). Sebaliknya, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, dan Bali menjadi provinsi dengan prevalensi filariasis limfatik terendah.
Pada tahun 2018 dilaporkan terdapat sebanyak 10.681 kasus kronis filariasis. Provinsi Papua menjadi provinsi dengan jumlah kasus kronik tertinggi dengan 3.615 kasus, diikuti Nusa Tenggara Timur dengan 1.542 kasus, Jawa Timur dengan 781 kasus, Papua Barat dengan 622 kasus, dan Aceh dengan 578 kasus.[1,2]
Indonesia menjadi satu-satunya negara di dunia yang memiliki tiga jenis parasit penyebab filariasis limfatik, yaitu Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, dan Brugia timori. Hal ini mencerminkan terjadinya cara penularan yang berbeda, sehingga strategi intervensi harus ikut disesuaikan. Bila tidak dikontrol dengan baik, disabilitas fisik berat akibat filariasis limfatik dapat menyebabkan hilangnya produktivitas dan mata pencaharian yang akan menambah beban ekonomi keluarga, masyarakat, juga negara.[1,3-5]
Global Program to Eliminate Lymphatic Filariasis (GPELF) yang diluncurkan WHO sejak tahun 2000 dengan target 2020 tidak dapat dicapai oleh Indonesia. Maka dari itu, WHO menetapkan target baru hingga 2030, yaitu untuk menurunkan hingga 80% kasus pada negara-negara endemis filariasis.[1,6]
Taeniasis dan Sistiserkosis
Taeniasis dan sistiserkosis adalah infeksi parasit yang disebabkan oleh cacing pita, yaitu cacing berbentuk pipih yang menyerupai pita atau plester. Tiga jenis cacing pita yang sering dijumpai di Indonesia adalah Taenia saginata dari daging sapi, Taenia solium dari daging babi, dan Diphyllobothrium latum dari ikan. WHO menyatakan bahwa taeniasis dan sistiserkosis adalah salah satu dari 17 penyakit tropis yang terabaikan, atau biasa disebut Neglected Tropical Diseases (NTD). Penularan terjadi melalui konsumsi daging hewan yang tak dimasak dengan sempurna. Dari ketiga jenis cacing yang menyebabkan taeniasis pada manusia, T. solium merupakan satu-satunya yang dapat menyebabkan sistiserkosis.[1,7]
Penduduk Indonesia mayoritas muslim dan cenderung lebih menyukai daging yang dimasak matang, sehingga taeniasis relatif lebih jarang ditemui di Indonesia. Meski begitu, telah dilaporkan infeksi taeniasis di Indonesia, yakni T. solium di Papua dan Bali; T. saginata di Bali; dan T. asiatica di Kepulauan Samosir dan desa Simalungun, Sumatera Utara. Taeniasis dan neurosistiserkosis juga pernah dilaporkan dari daerah Lampung, Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2017, studi oleh Zein et al mengonfirmasi sebanyak 171 karier taeniasis dari 180 suspek karier di Sumatera Utara.[1,8,9]
Khusus di Bali, dilaporkan bahwa infeksi oleh T.saginata berhubungan dengan kebiasaan penduduk lokal yang sering mengonsumsi daging sapi yang tidak dimasak atau disebut sebagai daging sapi lawar. Sebagian masyarakat Bali masih percaya bahwa otot yang terinfeksi sistiserkosis dari babi atau sapi disebabkan kekuatan jahat yang tak kasat mata, alih-alih faktor kebersihan dan kesehatan. Meski demikian, seiring kemajuan ekonomi yang menyebabkan diperbaikinya berbagai fasilitas umum, kasus infeksi taeniasis di Bali pun mulai menurun. Penularan aktif yang masih terjadi di Bali tampaknya hanya terbatas pada kecamatan Kubu dan kabupaten Karangasem.[1,8,10]
Taeniasis dan sistiserkosis berhubungan erat dengan faktor kemiskinan, kebersihan lingkungan dan individual, serta adat budaya yang berlaku pada masyarakat setempat. Program pengendalian apapun yang dirancang pemerintah harus bisa menyesuaikan dengan faktor-faktor tersebut. Suroso et al mengusulkan bahwa prioritas langkah yang harus dilakukan oleh pejabat pengambil keputusan program pengendalian taeniasis dan sistiserkosis adalah:
- Menemukan kasus secara aktif lalu mengobati mereka yang menjadi karier meski tidak mengalami gejala apapun
- Pendidikan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan untuk menerapkan perilaku kebersihan diri dan lingkungan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan kandang babi dan sapi yang berdekatan dengan tempat tinggal
- Melakukan surveilans ketat untuk mengidentifikasi dan mencatat kasus infeksi, serta memeriksa kualitas daging sapi atau babi yang beredar untuk dikonsumsi masyarakat sekitar
- Mendorong terciptanya komitmen politik dan kolaborasi antar sector, baik dalam skala lokal, nasional, dan internasional
Keterbatasan program penanggulangan dan pencegahan penyakit taeniasis atau sistiserkosis di Indonesia terutama disebabkan faktor budaya dan ekonomi. Banyaknya hewan ternak babi atau sapi yang menempati kandang di dekat rumah tanpa diperhatikan sanitasinya, serta kebiasaan daerah tertentu untuk memakan hasil olahan daging ternak tanpa memasaknya dengan matang sempurna, masih menjadi halangan eliminasi kasus taeniasis dan sistiserkosis di Indonesia.[7]
Schistosomiasis
Schistosomiasis adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing parasit yang hidup di air. Di Indonesia, parasit Schistosoma japonicum saat ini hanya ditemukan pada 3 area yang terisolasi di Lembah Lindu, Napu, dan Bada di provinsi Sulawesi Tengah. Penyakit ini telah menjadi masalah kesehatan masyarakat selama lebih dari 70 tahun sejak pertama kali ditemukan pada tahun 1937. Studi epidemiologi yang dilakukan di lokasi menyimpulkan bahwa hewan keong Oncomelania hupensis merupakan pejamu perantara yang ikut memfasilitasi penyebaran penyakit ini.[1,11]
Survei tahun 2008 hingga 2011 menunjukkan bahwa prevalensi schistosomiasis pada manusia berfluktuasi dengan kisaran 0,3% dan 4,8% di lembah Napu; serta 0,8% dan 3,6% di Lembah Lindu. Pada saat yang sama, persentase keong yang terinfeksi berkisar antara 1,7% dan 4% di Lembah Napu; serta 1,8% dan 3,6% di Lembah Lindu.
Pada tahun 2017, dilaporkan prevalensi schistosomiasis adalah 0,85% di Lembah Lindu dan 0,65% di Lembah Napu. Sementara itu, Lembah Bada memiliki tingkat prevalensi sebesar 0,97%. Dengan demikian, tingkat infeksi di 3 lembah endemis tadi < 1% di tahun 2017.[1,12,13]
Penyakit Infeksi Cacing Tanah
Penyakit infeksi cacing tanah, atau yang biasa disebut Soiled Transmitted Helminth (STH), merupakan sekelompok penyakit akibat cacing yang memerlukan media tanah untuk perkembangan bentuk infektifnya. Kondisi ini masih menjadi beban penyakit dunia dengan 1,45 miliar penderita di seluruh dunia. 70% dari kasus infeksi STH berada di Asia, dengan Asia Tenggara sebagai daerah tertinggi ditemukannya STH.
Terdapat 4 jenis cacing yang masuk ke dalam kelompok ini, yaitu Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Ancylostoma duodenale, dan Necator americanus. Indonesia mencatatkan penderita askariasis, trichuriasis, dan cacing tambang terbanyak di regio Asia Pasifik, dengan lebih dari 90 juta kasus untuk askariasis dan trichuriasis, serta 60 juta kasus cacing tambang.[1,14,15]
Infeksi STH cenderung dijumpai di daerah pedesaan dan memiliki prevalensi lebih tinggi pada anak-anak usia sekolah. Hal ini dikaitkan dengan perilaku bersih sehat atau personal hygiene yang belum sebaik orang dewasa, di samping faktor maturitas sistem imun. Rerata prevalensi infeksi STH pada anak usia sekolah di Indonesia antara tahun 2002 hingga 2009 dilaporkan sebesar 31,8%.
Di Nusa Tenggara Timur, provinsi termiskin nomor tiga skala nasional, prevalensi infeksi STH dilaporkan melebihi 20% di Sumba Barat pada tahun 2011. Desa Kalena Rongo yang merupakan desa termiskin di Sumba Barat Daya melaporkan prevalensi yang lebih tinggi, yaitu A. lumbricoides 65,8%, T. trichiura 60,4%, dan cacing tambang 53,5%.[1,14-19]
Kebijakan WHO dalam pengendalian infeksi STH mencakup pemberian obat cacing massal, penyediaan air bersih, kemudahan akses kebersihan, serta edukasi personal hygiene. WHO merekomendasikan pemberian obat cacing setahun sekali atau dua kali berupa albendazol 400 mg atau mebendazole 500 mg dosis tunggal untuk populasi yang berisiko tinggi, seperti anak usia sekolah dan prasekolah, anak remaja perempuan, dan wanita yang tidak sedang hamil. Indonesia telah menerapkan kebijakan deworming berupa pemberian obat albendazol pada semua anak usia sekolah setiap 6 bulan. [1,20] Meski demikian, target WHO berupa pencakupan ≥ 75% pemberian obat cacing tidak dapat dipenuhi oleh 23 negara di tahun 2018, salah satunya adalah Indonesia. [6]
Program Pengendalian oleh Pemerintah Indonesia
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Cacingan. Program Penanggulangan Cacingan ini diberi nama Reduksi Cacingan dan dimulai pada tahun 2019 yang terutama ditujukan untuk infeksi cacing tanah (STH) dan filariasis yang relatif masih tinggi kasusnya di seluruh provinsi Indonesia. Target dari program ini berupa penurunan prevalensi cacingan sampai di bawah 10% di setiap kabupaten atau kota.
Ada tiga hal utama yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kecacingan:
- Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) pada anak usia prasekolah dan sekolah
- Perbaikan kualitas air dan lingkungan bersih
- Melakukan sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat
POPM cacingan di Indonesia ditentukan pemberiannnya sebagai berikut:
- Bila prevalensi tinggi atau di atas 50%, maka POPM diberikan dua kali dalam satu tahun
- Bila prevalensi sedang (20-50%), maka POPM diberikan satu kali dalam satu tahun
Pelaksanaan POPM dilakukan bersamaan dengan program pemberian vitamin A dan pemberian makanan tambahan pada anak balita, usia prasekolah, dan sekolah. POPM cacingan wajib dilakukan secara terus menerus sampai terjadi penurunan prevalensi di bawah 10%.[21]
Kesimpulan
Data epidemiologi yang tersedia menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki tingkat infeksi cacing yang tinggi. Filariasis masih tersebar di seluruh Indonesia, dengan frekuensi kasus tertinggi didapatkan di Papua. Taeniasis juga masih dapat ditemukan, termasuk di Sumatera Utara, Bali, Papua, dan Nusa Tenggara. Selain itu, angka kejadian infeksi cacing tanah, seperti askariasis dan ankilostomiasis, di Indonesia masih dilaporkan sebagai salah satu yang paling tinggi di dunia.
Usaha pengendalian yang bisa dilakukan meliputi pemberian obat cacing profilaksis secara masal, perbaikan kualitas air dan lingkungan, serta edukasi terkait perilaku hidup bersih dan sehat. Dalam menyiapkan program pengendalian infeksi cacing, pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan aspek kultur dan budaya dari masyarakatnya yang ditengarai akan mempengaruhi proses penularan dan penyebaran infeksi cacing.