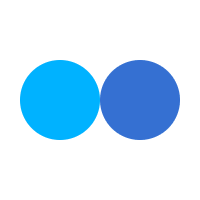Hingga saat ini, belum ada obat yang terbukti efektif sebagai terapi potensial untuk coronavirus disease 2019 atau COVID-19, menurut World Health Organization (WHO) dan Centers for Disease Control and Prevention (CDC).[1-3]
Sejumlah agen kerap diteliti dan dikembangkan, baik melalui uji klinis maupun program compassionate use (berdasarkan aktivitas in vitro) dan diharapkan dapat meningkatkan upaya pengendalian pandemi COVID-19. Artikel ini akan mengulas tentang sejumlah antivirus dan terapi suportif yang sedang dikembangkan yang bertujuan untuk mengobati COVID-19.[3,4]
Klorokuin dan Hidroksiklorokuin
Klorokuin dan hidroksiklorokuin merupakan obat yang umum digunakan pada malaria dan beberapa penyakit autoimun. Aktivitas antivirus klorokuin terhadap SARS-CoV-2 juga telah dilaporkan melalui studi in vitro. Selain itu, klorokuin juga dapat menginhibisi mekanisme badai sitokin pada COVID-19.[4,5]
Akan tetapi, uji klinis terkini justru tidak menemukan manfaat pemberian klorokuin/hidroksiklorokuin pada pasien COVID-19. Meta analisis yang dilakukan oleh Kashour z et al menyatakan bahwa klorokuin dan hidroksiklorokuin tidak memiliki manfaat signifikan untuk mengurangi penggunaan ventilasi mekanis, perawatan di ruang intensif, dan perawatan inap.[6]
Temuan serupa dikemukakan oleh Elavarasi et al dalam meta analisis. Penggunaan klorokuin/hidroksiklorokuin tidak memberikan efek signifikan dalam mengurangi mortalitas, waktu resolusi demam, atau perbaikan klinis ARDS.[7]
Uji acak terkontrol terbesar yang dilakukan oleh WHO, yaitu Solidarity trial mengonfirmasi bahwa hidroksiklorokuin tidak memberikan manfaat bermakna dalam durasi rawat inap dan inisiasi penggunaan ventilasi mekanis. Pemberian hidroksiklorokuin justru berkaitan dengan peningkatan risiko mortalitas jika dibandingkan dengan plasebo.[8]
Hasil serupa dilaporkan pula oleh RECOVERY trial. Pada grup yang mendapatkan hidroksiklorokuin, ditemukan frekuensi penggunaan ventilasi mekanis yang lebih tinggi. Sejumlah kecil kasus kematian akibat masalah jantung juga telah dilaporkan, walaupun tidak ada perbedaan pada insidensi aritmia jantung mayor pada kedua grup.[9]
Dengan demikian, WHO telah merekomendasikan untuk menghentikan penggunaan klorokuin dan hidroksiklorokuin pada COVID-19.[20] Sejalan dengan rekomendasi WHO, pedoman nasional juga telah mengeluarkan kedua agen ini dari terapi COVID-19.[10]
Lopinavir-Ritonavir
Lopinavir-ritonavir merupakan protease inhibitor yang telah digunakan untuk perawatan HIV. Studi in vitro dan percobaan pada binatang menunjukkan bahwa kombinasi kedua obat ini memiliki efek antivirus terhadap virus severe acute respiratory syndrome (SARS-CoV) dan virus middle east respiratory syndrome (MERS-CoV).[3,11,12]
Sebuah uji acak terkontrol yang dilakukan oleh Cao et al meneliti efikasi lopinavir-ritonavir yang dibandingkan dengan terapi standar. Hasil studi menunjukkan bahwa terapi lopinavir-ritonavir tidak berbeda signifikan dengan terapi standar dalam hal waktu perbaikan klinis dan mortalitas dalam 28 hari.[13]
Solidarity Trial mengemukakan bahwa lopinavir, baik secara tunggal maupun dikombinasikan dengan interferon, tidak memberikan dampak signifikan pada penurunan mortalitas, inisiasi ventilasi mekanis, dan durasi rawat inap.[8] Hasil serupa dilaporkan dalam RECOVERY trial, yaitu tidak ada perbedaan signifikan pada tingkat mortalitas, lama rawat inap, dan penggunaan ventilasi mekanis pada kedua grup.[14]
Saat ini, WHO telah merekomendasikan untuk menghentikan penggunaan lopinavir-ritonavir sebagai terapi pasien COVID-19.[15] Begitu pula pada pedoman nasional yang telah mengeksklusi lopinavir-ritonavir sebagai terapi COVID-19.[10]
Remdesivir
Remdesivir merupakan antivirus spektrum luas yang aktif terhadap Flaviviridae dan Coronaviridae, termasuk SARS-CoV dan MERS-CoV.[16,17]
Piscoya et al melakukan tinjauan sistematis dan meta analisis terhadap empat randomized controlled trial (RCT) yang membandingkan dengan total partisipan 2.296 pasien COVID-19 dan dua kasus serial yang membandingkan penggunaan remdesivir dengan terapi standar. Hasil penelitian menemukan bahwa remdesivir tidak mengurangi mortalitas semua sebab dalam 14 hari dan inisiasi ventilasi mekanis, jika dibandingkan dengan plasebo.[18]
Di sisi lainnya, meta analisis yang dilakukan oleh Yokoyama et al menemukan bahwa remdesivir menghasilkan perbaikan klinis yang cukup signifikan yang diobservasi pada hari ke-5 dan ke-10, jika dibandingkan dengan grup terapi standar.[19]
Hasil meta analisis 4 RCT yang dilakukan oleh Al-Abdouh et al menemukan bahwa tidak ada perbedaan bermakna pada mortalitas dalam 28–29 hari antara penggunaan remdesivir dan terapi standar pada pasien COVID-19 yang dirawat inap. Namun, jumlah pasien yang pulih dan dipulangkan lebih banyak pada grup remdesivir daripada grup kontrol.[20]
Sedangkan, hasil Solidarity Trial menemukan bahwa tidak ada perbedaan bermakna terhadap tingkat mortalitas pada grup remdesivir dan grup kontrol.[8] Dengan demikian, WHO tidak merekomendasikan penggunaan remdesivir pada pasien COVID-19.[21] Di lain sisi, CDC masih merekomendasikan remdesivir pada pasien COVID-19 yang dirawat inap dan menggunakan bantuan oksigen.[22]
Pedoman nasional Indonesia saat ini juga masih merekomendasikan remdesivir pada pasien COVID-19 kategori sedang, berat, dan kritis.[10]
Favipiravir
Data uji klinis favipiravir pada COVID-19 masih amat terbatas dan tidak menunjukkan hasil seragam. Belum lama ini, Cai et al melakukan RCT pada 80 pasien COVID-19 yang meneliti efektivitas favipiravir dan dibandingkan dengan lopinavir-ritonavir sebagai kontrol.[23]
Kedua grup mendapatkan terapi pelengkap interferon alfa via inhalasi aerosol. Mereka melaporkan bahwa waktu klirens virus ditemukan lebih singkat pada grup favipiravir daripada grup kontrol. Hasil serupa ditemukan pula dalam aspek perbaikan pada pencitraan toraks, dengan improvement rate 91,43% vs 62,22% untuk keunggulan favipiravir.[23]
RCT lain juga dilakukan oleh Chen et al pada 240 pasien COVID-19, yang meneliti efektivitas favipiravir dan dibandingkan dengan arbidol. Hasilnya, tidak terdapat perbedaan bermakna pada perbaikan klinis pada hari ke-7 di antara kedua grup.[24]
Hasil studi observasional di Jepang pada total 2.158 kasus menunjukkan bahwa penggunaan favipiravir berhubungan dengan perbaikan klinis pada hari ke-7 dan hari ke-14, baik pada kasus COVID-19 ringan, sedang, maupun berat. Studi ini juga melaporkan efek samping favipiravir, yaitu hiperurisemia, diare, penurunan hitung neutrofil, transaminitis, dan berpotensi teratogenik.[25]
Meta analisis yang dilakukan oleh Wei et al dan Shrestha et al juga turut memberikan hasil yang serupa.[46,47] Namun, Shrestha et al juga menambahkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan terhadap bersihan virus, penggunaan ventilasi noninvasif, dan efek samping pada kedua grup.[27]
Pedoman nasional masih merekomendasikan penggunaan favipiravir sebagai terapi COVID-19 dengan derajat ringan hingga kritis. Favipiravir tidak direkomendasikan pada wanita hamil, wanita yang merencanakan kehamilan, dan pasien dengan gangguan fungsi hati berat.[10]
Oseltamivir
Oseltamivir merupakan inhibitor neuraminidase. Obat ini sudah disahkan untuk penanganan influenza, tetapi belum untuk COVID-19. Belum tersedia data in vitro tentang aktivitas oseltamivir terhadap SARS-CoV-2. Pada awal pandemi, oseltamivir digunakan sebagai terapi COVID-19 di Cina karena saat itu negara tersebut sedang memasuki puncak musim influenza.[28,29]
Sejumlah uji klinis saat ini memasukkan oseltamivir pada grup kontrol, tetapi bukan dimaksudkan sebagai terapi intervensi yang diuji. Agen ini tidak mempunyai peran dalam terapi COVID-19 begitu diagnosis influenza dapat disingkirkan.[29]
Pedoman nasional merekomendasikan penggunaan oseltamivir pada kasus COVID-19 ringan jika ada indikasi influenza.[10]
Umifenovir
Umifenovir, atau yang dikenal dengan arbidol, merupakan agen antivirus yang memiliki mekanisme menargetkan S protein/ ACE interaction dan menginhibisi fusi membran dari envelope virus.[30] Agen ini sudah disahkan di Rusia dan Cina sebagai terapi dan profilaksis influenza. Data in vitro awal menunjukkan adanya aktivitas antiviral terhadap SARS, sehingga obat ini sedang diteliti sebagai terapi COVID-19.[29]
Sebuah studi observasional nonacak pada 67 pasien COVID-19 di Wuhan menunjukkan bahwa umifenovir dengan durasi median 9 hari berhubungan dengan tingkat mortalitas rendah dan angka rawat jalan yang lebih tinggi daripada grup kontrol.[29,31]
Hasil meta analisis yang dilakukan oleh Huang et al terhadap 12 studi menemukan bahwa penggunaan umifenovir berhubungan dengan tingkat PCR yang negatif pada hari ke-14. Namun, penggunaan umifenovir tidak berhubungan dengan perbaikan demam pada hari ke-7, perbaikan batuk pada hari ke-7, atau pengurangan lama rawat inap. Kesimpulannya, bukti klinis yang menyokong efikasi umifenovir pada perbaikan luaran COVID-19 masih kurang.[32]
Nitazoxanide
Nitazoxanide merupakan agen antihelmintik yang juga secara in vitro mempunyai aktivitas antivirus, termasuk terhadap MERS-CoV dan SARS-CoV-2.[29,33]
Dalam sebuah laporan kasus, Calderon et al menyatakan bahwa terdapat luaran positif setelah pemberian nitazoxanide pada 16 pasien COVID-19 yang dirawat jalan. Namun, sampai saat ini, belum ada RCT yang meneliti efikasi nitazoxanide pada COVID-19.[34]
Camostat Mesylate
Camostat mesylate merupakan obat yang disahkan sebagai terapi pankreatitis di Jepang. Studi in vitro menemukan bahwa agen ini dapat mencegah masuknya SARS-CoV-2 ke dalam sel.[35]
Belum ada RCT yang meneliti tentang obat ini, tetapi laporan kasus serial retrospektif di Jerman menunjukkan bahwa penggunaan compassionate camostat mesylate selama 8 hari dapat mengurangi derajat keparahan COVID-19 pada pasien yang dirawat di ruang intensif, yang dinilai dengan sepsis-related organ failure assessment score (SOFA).[ [29,36]
Ivermectin
Latar belakang penggunaan ivermectin sebagai profilaksis dan terapi COVID-19 didasari oleh laporan studi in vitro, di mana ivermectin dapat menginhibisi importin alpha/beta-1 nuclear transport protein inang. Protein ini merupakan kunci proses transpor intraseluler yang “dibajak” oleh virus, sehingga terjadi peningkatan infeksi akibat supresi respons antivirus inang.[37,38]
Selain itu, studi in vitro lain menunjukkan bahwa docking ivermectin dapat mengganggu proses penempelan protein spike SARS-CoV-2 pada membran sel manusia. [59] Meskipun demikian, studi farmakokinetik dan farmakodinamik memperlihatkan bahwa dibutuhkan dosis ivermectin hingga 100 kali lipat lebih tinggi (daripada yang disahkan saat ini untuk manusia) untuk mencapai konsentrasi plasma yang cukup untuk mencapai aktivitas antivirusnya.[39,40]
Berbeda dari hasil in vitro, sejumlah hasil studi klinis malah menunjukkan hasil yang kontradiktif. Data studi yang ada pun masih menunjukkan banyak limitasi, baik akibat kurangnya jumlah sampel, desain studi yang masih label terbuka, maupun tidak adanya deskripsi derajat keparahan COVID-19. Oleh karena itu, ivermectin belum direkomendasikan sebagai terapi COVID-19.[41]
Interleukin Inhibitor
Pertimbangan penggunaan interleukin inhibitor pada COVID-19 didasarkan pada patofisiologi kerusakan jaringan dan organ akibat respons imun berlebihan.[29,42,43]
Tocilizumab telah digunakan pada sejumlah kasus COVID-19. Laporan kasus dari 21 pasien COVID-19 menunjukkan bahwa pemberian tocilizumab dosis tunggal berhubungan dengan perbaikan fungsi respirasi pada 91% pasien, perbaikan demam, dan penurunan angka rawat jalan.[29,44]
Meta analisis yang dilakukan oleh Shao-Huan et al menunjukkan bahwa mortalitas semua sebab lebih rendah pada grup tocilizumab daripada grup kontrol (16,3% vs 24,1%), walaupun tidak bermakna secara statistik. Tidak ditemukan pula perbedaan bermakna pada risiko perawatan di ruang rawat intensif dan kebutuhan penggunaan ventilasi mekanis di antara grup intervensi dengan grup kontrol.[45]
Meta analisis yang dilakukan oleh Tleyjeh et al melaporkan bahwa tocilizumab bermanfaat untuk menurunkan risiko penggunaan ventilasi mekanis dan mortalitas. Hasil tersebut terlihat konsisten pada semua derajat keparahan COVID-19.[46] Saat ini, tocilizumab sudah disahkan dalam pedoman terapi di Cina.[47]
Interleukin-1 inhibitor (anakinra) telah diujicobakan pada sejumlah kasus COVID-19. Studi kohort retrospektif di Italia melaporkan bahwa pemberian anakinra dosis tinggi berhubungan dengan penurunan kadar serum C-reactive protein dan perbaikan fungsi respirasi pada 72% pasien COVID-19 dengan ventilasi noninvasif. Setelah 21 hari, ditemukan tingkat kesintasan sebesar 90% pada grup anakinra dosis tinggi vs 56% pada grup terapi standar.[48,49]
Studi lainnya di Paris melaporkan bahwa pemberian anakinra dapat mengurangi kebutuhan ventilasi mekanis pada pasien COVID-19 yang di ruang rawat intensif.[50]
Hasil studi fase III CAN-COVID, yang menginvestigasi pemberian canakinumab pada pasien COVID-19, menemukan bahwa pemberian canakinumab yang disertai terapi standar tidak memperbaiki tingkat kesintasan atau kebutuhan ventilasi mekanis. Saat ini, sedang berlangsung uji klinis untuk obat interleukin inhibitor lainnya, seperti sarilumab.[48,51]
Inhibitor Janus Kinase (JAK) dan Numb-Associated Kinase (NAK)
Studi in vitro menunjukkan bahwa inhibisi NAK dapat mencegah masuknya virus ke dalam sel. Salah satu dari agen yang sedang diteliti adalah baricitinib (inhibitor JAK dan inhibitor NAK, dengan afinitas tinggi AAK1).[52]
Sebuah studi telah menginvestigasi efek pemberian baricitinib pada pasien yang juga diberikan remdesivir dan dibandingkan dengan plasebo. Hasilnya, grup yang mendapatkan baricitinib rata-rata mengalami pemulihan dalam 7 hari, sedangkan rerata lama pemulihan pada grup plasebo adalah 8 hari.
Waktu pemulihan yang lebih singkat juga terlihat pada pasien yang menerima oksigen aliran tinggi dan ventilasi noninvasif dibandingkan dengan grup kontrol (10 hari vs 18 hari).[53]
Saat ini, kombinasi baricitinib dan remdesivir telah mendapat ijin penggunaan darurat dari FDA sebagai terapi COVID-19 pada pasien yang membutuhkan suplementasi oksigen, ventilasi mekanis, atau extracorporeal membrane oxygenation (ECMO).[54]
Interferon Tipe I (IFN-I)
Sejumlah studi in vitro dan in vivo telah meneliti penggunaan IFN-1 pada MERS-CoV dan SARS-CoV. Hipotesis tersebut berhubungan dengan aktivitas protektif IFN beta 1 di paru-paru, yaitu mereduksi kebocoran vaskuler pada acute respiratory distress syndrome.[55]
Walz Lucas et al melakukan meta analisis terhadap inhibitor Janus kinase (JAK) dan interferon tipe 1 pada pasien COVID-19. Hasil studi menemukan bahwa jika dibandingkan dengan grup plasebo, resipien inhibitor JAK mengalami penurunan risiko mortalitas, penurunan perawatan intensif, serta peningkatan jumlah pasien yang dipulangkan. Hal serupa ditemukan pula pada grup resipien interferon tipe I.[56]
Terapi Imunoglobulin
Terapi imunoglobulin pada COVID-19 meliputi plasma konvalesen dan hyperimmune immunoglobulin intravena (IVIg).[49,82] Antibodi dari pasien COVID-19 yang sudah sembuh diharapkan dapat membantu bersihan virus pasien COVID-19.
Hal tersebut didukung oleh laporan sistematis dan meta analisis eksplorasi yang dilakukan oleh Mair-Jenkins et al terhadap 8 studi observasional dari 714 pasien SARS. Studi ini menunjukkan bahwa pemberian plasma konvalesen dan IVIg berhubungan dengan penurunan mortalitas. Namun, kualitas studi dinilai masih rendah dan memiliki risiko bias publikasi.[57]
Secara teori, terapi imunoglobulin bermanfaat pada 7–10 hari infeksi COVID-19, di mana viremia mencapai puncak dan respons imun belum optimal.[29]
Meher Bikash et al melakukan meta analisis terhadap data 2 RCT dan 4 studi observasional dengan total 474 pasien yang mendapat terapi plasma konvalesen. Peneliti menemukan bahwa pada grup yang mendapatkan plasma konvalesen, terdapat penurunan mortalitas, perbaikan klinis, dan peningkatan early viral clearance di hari ke-7.[58]
Laporan kasus serial dari 3 pasien COVID-19 menunjukkan pemulihan klinis, resolusi hasil radiografi, dan konversi negatif tes PCR pada grup yang diberikan IVIg. Tidak efek samping serius yang dilaporkan. Saat ini, masih berlangsung uji acak terkontrol yang mengevaluasi efikasi IVIg pada pasien COVID-19 yang kritis.[29,59]
FDA telah mengeluarkan izin penggunaan darurat plasma konvalesen sebagai terapi COVID-19.[84] Pedoman nasional Indonesia merekomendasikan plasma konvalesen untuk COVID-19 derajat sedang dan berat. Sedangkan, IVIg dapat dipertimbangkan pada pasien COVID-19 derajat berat dan kritis.[10]
Azithromycin
Azithromycin dipakai untuk menangani superinfeksi bakteri pada COVID-19. Selain itu, azithromycin juga diduga bermanfaat dalam mengurangi respons inflamasi, menginhibisi hipersekresi mukus, menurunkan reactive oxygen species, mempercepat apoptosis neutrofil, dan memblokir aktivasi faktor transkripsi nukleus.[3,61,62]
Data klinis efikasi azithromycin pada COVID-19 masih terbatas. Studi nonacak di Perancis meneliti 26 pasien yang diberikan hidroksiklorokuin sulfat, dengan 6 pasien diantaranya diberikan tambahan azithromycin untuk mencegah superinfeksi bakteri. Peneliti melaporkan bahwa semua pasien yang mendapatkan kombinasi azithromycin dan hidroksiklorokuin menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan pasien yang hanya mendapatkan hidroksiklorokuin.[3,63]
Efek samping pemberian azithromycin adalah risiko aritmia akibat pemanjangan interval QT.[3, 22] Data terbaru dari RECOVERY trial menemukan bahwa azithromycin tidak memiliki manfaat signifikan pada pasien COVID-19 yang dirawat inap, baik dalam mortalitas 28 hari, pemulangan pasien dalam kondisi hidup, dan penggunaan ventilasi mekanis.[64]
Kolkisin
Kolkisin dapat menginhibisi sitokin yang terlibat pada kerusakan paru akut. Sebuah RCT melaporkan bahwa rerata lama penggunaan oksigen lebih rendah pada grup kolkisin daripada grup kontrol (3 hari vs 7 hari). Hal serupa juga ditunjukkan pada rerata lama rawat inap, yaitu 6 hari pada grup kolkisin dan 8,5 hari pada grup kontrol. Mayoritas efek samping yang terjadi pada grup kolkisin adalah diare.[64-67]
Terapi Nutrisi Penunjang
Potensi vitamin C pada terapi COVID-19 dilatarbelakangi oleh efek imunomodulator dan antioksidannya. Temuan studi awal yang dilakukan oleh Marik et al menunjukkan bahwa pemberian vitamin C dikombinasikan dengan hidrokortison dan tiamin (vitamin B1) dapat mencegah pemburukan disfungsi organ dan mengurangi mortalitas pada pasien sepsis berat dan syok sepsis.[68]
Studi lainnya menemukan keuntungan vitamin C dalam hal vasopressor sparing effects dan mengurangi kebutuhan ventilasi mekanik dan lama rawat di ruang intensif.[69,70] Baladia et al meninjau bahwa data klinis dari 95 studi yang tersedia masih kurang untuk menyokong penggunaan vitamin C sebagai terapi COVID-19.[71]
Vitamin D juga telah digunakan sebagai terapi suportif pada COVID-19. Studi kohort retrospektif menemukan bahwa individu dengan defisiensi vitamin D memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami COVID-19 jika dibandingkan dengan individu dengan kadar vitamin D yang adekuat.[72]
Vitamin C dan vitamin D telah digunakan sebagai terapi pendamping pada tata laksana COVID-19 di Indonesia.[10]
Kesimpulan
Hingga saat ini, belum tersedia obat antivirus yang benar-benar terbukti memberi manfaat signifikan pada tata laksana COVID-19. Meski demikian, sejumlah opsi dapat digunakan secara terbatas, baik dalam lingkup tujuan penelitian ataupun compassionate use) dalam pengawasan tim medis, sesuai pedoman yang berlaku di negara masing-masing. Saat ini, remdesivir, favipiravir, oseltamivir, azithromycin, vitamin C, vitamin D telah diaplikasikan pada protokol terapi COVID-19 di Indonesia.